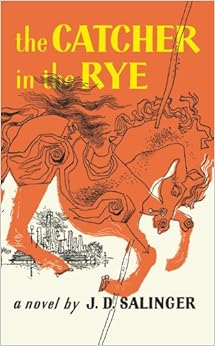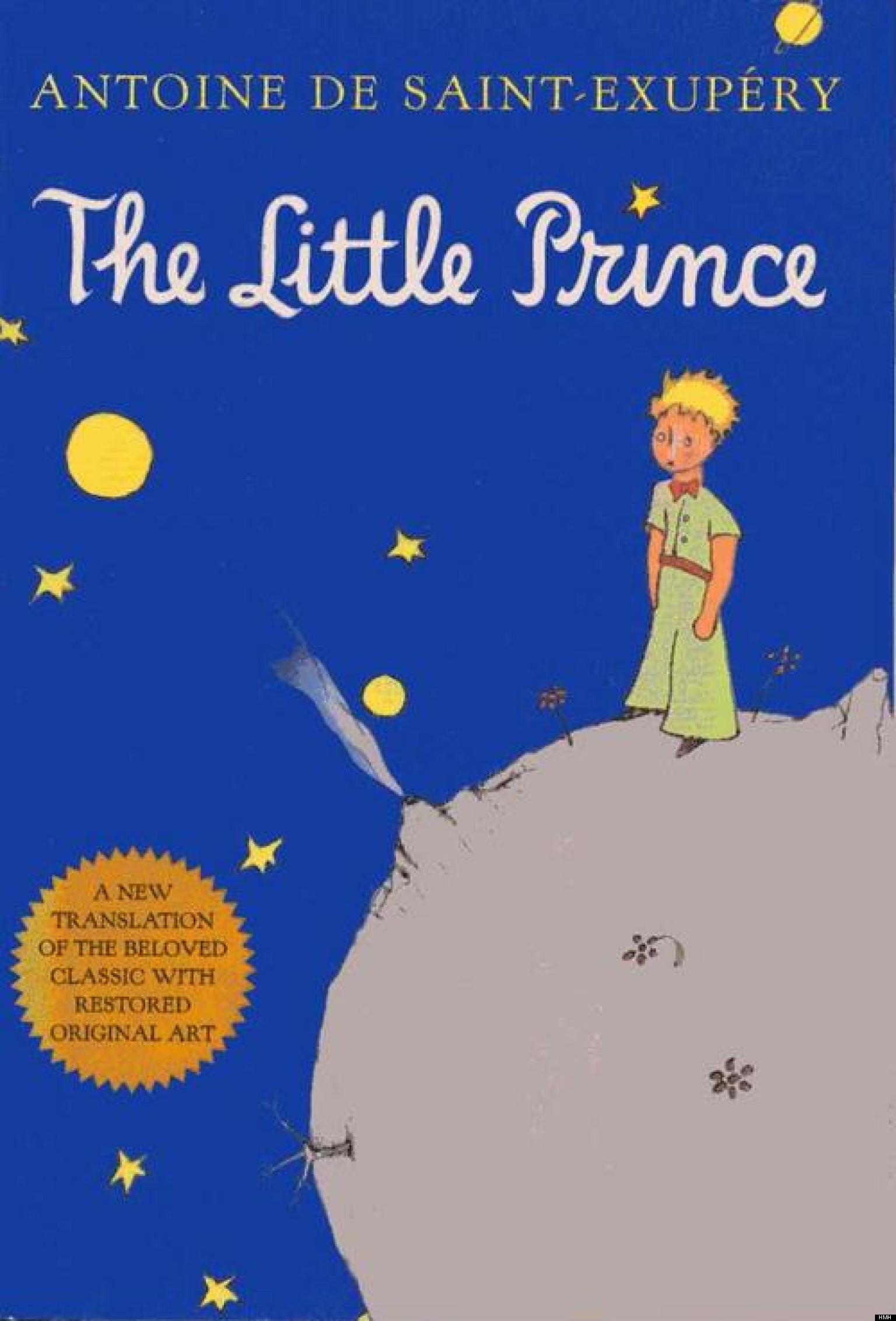Sebagai pecinta buku dan pecinta kutipan-kutipan mengenai buku, gue pernah merasa kesal membaca kutipan di atas karena belum pernah traveling. Saat itu gue berpikir tidak akan bisa traveling. Gue selalu sulit mendapat izin orang tua. Namun, seiring pertambahan usia, gue akhirnya mendapat izin untuk bepergian dan berangkatlah gue ke Singapura.
Gue tahu, Singapura bukan lagi tujuan asing bagi sebagian besar orang Indonesia (dan mungkin juga sebagian besar masyarakat dunia). Siapa yang tidak kenal Orchard Road dan Little India? Siapa tidak pernah mendengar tentang Patung Merlion? Sedikitnya, orang pasti pernah ke Singapura minimal satu kali. Bahkan bagi gue, perjalanan kemarin ini bukan yang pertama kalinya. Dulu, meski hanya setengah hari, gue sudah pernah merasakan makan di Little India dan mengunjungi Jurong Bird Park.
Meski begitu, perjalanan kemarin adalah kali pertama gue benar-benar berkeliling Singapura.
Kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.20. Karena Singapura tidak terlalu jauh, perjalanan hanya memakan waktu kurang lebih satu jam. Di pesawat, tempat duduk kami terpisah. Dua teman gue duduk bersama, sedangkan gue duduk di sebelah seorang nenek yang berasal dari Cibinong.
Seperti biasa kalau suasana hati gue sedang baik, gue bersedia bercakap-cakap (bahkan memulai percakapan) dengan orang asing. Begitu juga yang terjadi dengan si nenek ini. Beliau bercerita tentang tujuannya pergi ke Singapura, yaitu untuk mengunjungi besannya. Katanya, karena disibukkan dengan toko di Cibinong, mereka baru sempat pergi ke Singapura hari itu untuk halal bi halal. Awalnya gue pikir, langka sekali ada keluarga Muslim di Sngapura. Namun, ternyata memang begitu adanya (yang berarti pemikiran gue didasari oleh prasangka semata), dan justru (ini yang menarik) keluarga si nenek sebenarnya Katolik. Anak perempuannya menjadi mualaf setelah bertemu dengan suaminya. Kenapa menarik? Karena setahu gue, pemeluk agama Katolik sama taatnya dengan pemeluk agama Islam sehingga sulit dibayangkan bisa ada yang pindah agama. Tapi, begitulah adanya, dan itu membuktikan kepada saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin.
Sang nenek sangatlah baik. Beliau menawarkan gue makanan, yang jelas gue terima dengan senang hati karena gue memang lapar pada saat itu. Kemudian, saat gue kebingungan mengisi formulir imigrasi (karena itu adalah saat pertama bagi gue), beliau bahkan menawarkan formulir imigrasi anaknya untuk gue lihat sebagai contoh. Beliau bercerita bahwa dulu beliau pun sering bepergian bersama teman-teman ke luar negeri, tapi itu sudah lama sekali ketika masih muda. Sekarang, beliau sudah lupa cara mengisi formulir imigrasi. Gue menikmati perjalanan sambil mengobrol dengan beliau.
Setelah membeli
tourist pass, kami segera bergerak menuju halte MRT Lavender, karena penginapan kami berada di sekitar situ. Kami berencana untuk menaruh barang, lalu segera pergi. Karena kami hanya punya waktu tiga hari di Singapura, kami harus memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya.
Nama penginapan kami adalah Gusti Bed and Breakfast. Pemiliknya bisa berbahasa Indonesia (dan menurut salah satu teman, di daerah itu memang ada banyak orang Indonesia), dan konon suaminya orang Bali. Namun, gue tidak bertanya-tanya lebih lanjut mengenai ini.
Satu hal yang menarik dari penginapan itu adalah dia berfungsi sebagai
shared room. Artinya, nanti kami akan berbagi kamar dengan turis-turis lain, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Laki-laki ataupun perempuan akan ditempatkan seadanya kamar kosong, yang berarti kami tidak bisa terlalu pilih-pilih. Awalnya, gue khawatir dengan keamanannya. Tapi, prospek bertemu
traveler lain terlalu menyenangkan untuk diabaikan.
Saat kami tiba di sana, kamar kami kosong. Hanya ada sebuah koper dengan
name tag yang menunjukkan nama yang sangat Indonesia. Kebetulan juga, kata si pemilik, hanya ada perempuan di kamar kami. Kami meletakkan barang-barang, kemudian segera pergi untuk petualangan pertama kami.
Makan di Little India
Menurut Google, ada Festival Makanan Singapura hari itu. Karena kami bingung mau makan apa dan festival makanan terdengar menarik, kami memutuskan akan mengunjungi festival itu terlebih dulu. Namun, di Google, tidak ada lokasi jelas mengenai keberadaan si festival. Kami bertanya pada pemilik penginapan, katanya terletak di seberang Bugis Junction. Itulah alasan Bugis Street jadi tempat pertama yang kami kunjungi.
Namun, saat kami tiba di Bugis Street, tidak terlihat adanya festival makanan. Kami memutuskan untuk bertanya pada salesperson yang sedang membagi-bagikan pamflet di depan Bugis Junction. Dia sangat baik; dia tidak tahu juga tentang lokasinya, tapi dia berusaha mencarikan di internet. Sayangnya, tidak ada petunjuk jelas mengenai si festival. Hingga hari ini, kami masih bingung festival itu ada di mana.
Karena lapar, kami akhirnya memutuskan makan yang paling aman kehalalannya, yaitu restoran vegetarian di Little India. Kami dipandu ke sana oleh seorang guru seni yang kami temui di jalan. Fara yang bertanya padanya. Dia merekomendasikan restoran Komala Villas. Jadilah, makanan pertama kami di Singapura adalah makanan India.
 |
| Chappati plate dan set nasi biryani |
Meski kurang cocok di lidah gue, sehingga gue tidak bisa makan terlalu banyak, gue mau makan makanan India lagi dan lagi. Ini kedua kalinya gue makan set nasi
biryani; yang pertama di restoran India vegetarian yang terletak tidak jauh dari Komala Villas, yaitu Ananda Bhavan. Rasanya kurang lebih sama.
Kesan gue saat berada di Little India adalah bahwa tempat itu sangat ramai. Gue tidak tahu seperti apa aslinya rupa kota di India, tapi Little India sendiri jelas berbeda dari tempat-tempat lain di Singapura yang nanti satu per satu akan gue ceritakan. Di Little India, pasar segar - atau kios-kios yang menjual buah, paling tidak - cukup banyak terlihat. Kemudian, banyak penjual gelang-gelang manik-manik. Lalu, ada wangi dupa atau semacamnya (?) yang cukup kentara di tiap toko yang kami kunjungi.
Laser Show @ Marina Bay Sands
Kami tidak menghabiskan banyak waktu di Little India karena konon ada pertunjukkan laser di Marina Bay Sands. Jadi, kami naik MRT ke sana. Kendaraan umum di Singapura, jika dibandingkan dengan di Indonesia, jauh sekali bedanya. Di sana, kendaraan umum memfasilitasi warga lokal maupun turis dengan sangat baik. Petunjuknya jelas dan mudah dimengerti. Kita hanya perlu membaca. Ditambah lagi, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa dominan di sana sehingga untuk menanyakan arah bisa lebih mudah. Warga Singapura pun, mungkin karena Singapura adalah negara yang banyak dikunjungi, terbuka terhadap turis dan sangat membantu.
Pokoknya, malam itu, dengan mudah kami mencapai Marina Bay Sands. Dari stasiun MRT ke lokasi pertunjukan, kami berjalan kaki. Menurut gue, jaraknya tidak terlalu jauh. Jalanan di sana rapi dan lebih kosong daripada jalanan Jakarta, jadi kondisi untuk jalan kaki pun lebih nyaman.
Sesampainya di lokasi, kami disambut oleh gemerlap lampu hias tersebar di seluruh area. Ada patung-patung angka yang menunjukkan pertumbuhan negara Singapura. Ada musisi jalanan yang memainkan alat musik tradisional China. Ada bangku-bangku santai tempat berbaring menikmati sungai (atau laut?) di malam hari yang dikelilingi lampu-lampu bangunan pencakar langit Singapura.
Suasana seperti itu saja sudah indah buat gue, meski terlalu romantis untuk dinikmati bersama teman-teman sesama jomblo, tapi pertunjukkan lasernya jauh lebih indah. Luar biasa!
Anyway, kami harus segera pulang karena takut ketinggalan MRT terakhir. Jadilah kami tidak menonton pertunjukkan lasernya hingga akhir. Sebelum pulang, kami sempatkan mengejar foto dengan bianglala dan Esplanade yang terlihat seperti durian raksasa dari kejauhan. Mungkin karena capek setelah seharian bergerak nonstop, gue sedikit sebal karena sedikit-sedikit harus foto. Gue yang tidak suka durian jadi semakin sebal dengan durian karena seseorang memastikan dirinya foto dengan Esplanade sebagai latar dari berbagai sisi. Tapi, ini baru setengah hari pertama. Buat apa bersungut-sungut karena itu?
Teman-teman seperjalanan gue mengeluh kaki mereka sakit karena alas kaki yang mereka gunakan kurang memadai dari segi kenyamanan. Tapi, apa daya, kami harus berjalan agar sampai ke penginapan. Meski pelan-pelan, akhirnya kami tiba di stasiun MRT dan kemudian naik MRT sampai di Stasiun Lavender yang berada di dekat penginapan. Dari sana, kami jalan lagi ke penginapan.
First Roommates
Kami bertanya-tanya siapa yang akan jadi teman sekamar kami. Jelas sekali orang Indonesia, tapi orang yang seperti apa? Saat kami tiba di kamar, ternyata mereka adalah cewek-cewek seusia kami. Awalnya, kami merasa senang karena teman seusia berarti teman. Namun, setelah mengamati, mereka ini ternyata semacam
snob. Tanpa maksud mendiskreditkan anak-anak gaul, karena gaul itu boleh saja dan malah keren di saat-saat tertentu, di mata gue saat itu, mereka ini cuma tahu gaul. Sedikit bodoh dan jelas
ignorant meski katanya mereka lulusan universitas ternama.
Bagi gue,
shared room berarti kita harus berinteraksi dengan penghuni kamar selain kita. Buat apa pilih
shared room kalau kita mau memperlakukan kamar seolah itu hanya dihuni oleh kita dan teman-teman kita?
Shared room tidak seperti kendaraan umum di mana kita bisa duduk tanpa menyapa kanan-kiri. Kalau mau begitu, ada baiknya silakan saja menyewa kamar pribadi.
Tapi, karena memiliki pendapat berbeda itu sah-sah saja, jadi gue harus memaklumi mereka yang kelihatannya memiliki pendapat berbeda ini. Sebelumnya, dari mana gue tahu mereka punya pendapat berbeda? Alkisah, di kamar itu ada penghuni lain seperti mereka, yaitu seorang bapak yang tidak kelihatan rupanya karena konon pergi dari pagi hingga larut malam. Sepertinya ada kesalahpahaman antara pemilik penginapan dengan si bapak, karena pemilik penginapan memberikan tempat tidur si bapak untuk gue. Jadilah gue bertanya-tanya pada cewek-cewek ini tentang teman sekamar mereka. Ternyata, cewek-cewek ini tidak tahu-menahu tentang si bapak.
Ada hal yang lucu tentang ini. Cewek-cewek itu bilang mereka suka menggosipkan si bapak yang konon mengorok dengan keras. Gue diam saja karena gue saat itu sedang dalam mode pengamatan; gue belum tahu kisah mereka. Lalu, karena gue perlu berinteraksi dengan si bapak mengenai masalah tempat tidur itu, gue mengajaknya ngobrol. Awalnya, dalam bahasa Inggris. Kemudian, dalam bahasa Indonesia. Ternyata si bapak adalah orang Indonesia! Gue berpikir, bagaimana perasaan cewek-cewek itu begitu tahu si bapak orang Indonesia.
Hal lucu kedua tentang gosip cewek-cewek itu adalah karena ternyata dua dari mereka mengorok dengan jauh lebih keras daripada si bapak. Mereka itu sekumpulan lelucon.
Kekesalan gue terhadap cewek-cewek itu didasari oleh kesan tidak sopan yang mereka tampilkan. Tanpa izin, mereka memakai
extension colokan yang ada di kamar. Kami pikir itu punya mereka, mereka pikir itu punya kami. Ternyata itu punya si bapak. Kalau mereka sopan, tentu mereka akan meminta izin dulu kepada kami kalau mereka benar berpikir itu punya kami. Sekarang, itu ternyata punya si bapak, dan bahkan setelah mereka tahu, mereka bersikap seolah mereka tidak mendengar. Bicaranya, sih, mau belanja di Sephora, mau naik taksi ke sana dan ke sini, pamer ini-itu ke sosial media... tapi dengan sopan-santun minus seperti itu, kalau gue jadi mereka, gue akan malu.
Ditambah lagi, mereka sangat menyebalkan soal miskomunikasi tempat tidur itu. Tipikal orang yang hanya banyak bicara tanpa memberikan solusi. Tapi, sungguh, kekesalan gue menguap begitu gue mendengar cewek-cewek itu mengorok dengan keras. Bukan karena mengoroknya, karena semua orang bisa mengorok, gue pun begitu - tapi lebih karena mereka SANGAT termakan omongan sendiri. Sungguh, lain kali gue mungkin lebih baik ikut bergosip dengan mereka tentang mereka sendiri. Betapa lucunya.